Melepaskan [Cerpen]
Gambar dari sini
Diyanti tak lantas percaya ketika banyak orang yang
mengatakan padanya bahwa hidup ini sederhana dan begitu mudah untuk dilewati.
Buktinya ketika kali ini dia dihadapkan pada sebuah kenyataan pahit, batinnya
seketika menjerit. Segala filosofi tentang kesederhanaan hidup, melepaskan dan
mengikhlaskan tiba-tiba lenyap. Kali ini dia benar-benar merasa sulit
melangkah.
Sejam sebelum jam kuliahnya dimulai, dia sudah menyeruput
secangkir kopi di sebuah warung berbilik bambu di pinggir sebuah jalan
alternatif di tengah kota Bandung tak jauh dari kampusnya. Warung kopi ini
memang tersembunyi, yang datang kesini hanya karyawan dari pabrik yang menjamur
di sekitar sini.
Hanya butuh waktu tiga menit menunggu, secangkir kopi hitam
yang diseduh dengan air panas setengah dari takaran lazimnya sudah terhidang di
meja. Sang pemilik warung sudah maklum dengan pesanan anak muda yang satu ini.
Diyanti tidak lantas menyentuh cangkir itu, tidak sekarang
ketika asap masih mengepul dan aroma kopi menyeruak membungkus udara, tidak
juga tiga puluh menit kemudian, ketika asap itu sudah tidak lagi terlihat dan
suhu secangkir kopi itu sudah setara dengan udara sekitar.
Warung kopi itu masih sepi, hanya ada Diyanti yang duduk di
bangku paling ujung, bangku yang menghadap langsung ke arah jalan dengan
kendaraan berseliweran. Kedua bola matanya hanya memandang lurus ke jalan di
depan warung itu dan tanpa aba-aba meneteslah buliran bening di pipinya. Diyanti
membiarkannya, dan tak melakukan upaya apapun seperti segera ia mengusapnya
dengan ujung lengan kemejanya atau mencari tisu. Ada rasa perih yang
menggelanyut di dadanya yang membuat ia tak mampu menahan diri untuk tidak
menangis.
Sang pemilik warung mendekati tempat duduk Diyanti, dia
duduk tepat di hadapannya dan menghalanginya dari pemandangan jalanan. Pemilik
warung itu mengenal Diyanti bukan hanya sebagai pelanggan kopi di warungnya.
“Sudahlah nak, tak perlu kau tangisi kepergian kakakmu.”
Kalimat itu meluncur seketika dan membuat Diyanti tersentak.
“Dari mana bapak tahu tentang kematian kakak saya?”
memandang dengan penuh tanya dan pipi yang masih berurai air mata.
Pemilik warung hanya tersenyum dan memalingkan wajah seraya
berujar “Untuk apa kau menangis?”
“Wajar saja saya menangis, saya telah kehilangan orang yang
tak hanya menjadi kakak tetapi juga ayah dan ibu bagi saya. Setelah lelaki yang
harusnya kupanggil ayah minggat dari rumah, ibu mulai sakit-sakitan dan tak
mampu lagi bertahan. Sejak saat itu aku hanya memilikinya dan kini dia sudah
pergi.” Kalimat terpanjang yang mampu Diyanti keluarkan sebagai pembelaan.
“Aku bertanya untuk apa? Untuk siapa? Apakah karena kau
benar-benar sayang kepada kakakmu? Kau menghawatirkan keadaannya di alam sana?
Atau kau menangis karena kau iba pada dirimu sendiri?”
Untuk kesekian kalinya Diyanti tersentak dan mulai tidak nyaman dengan
kehadiran bapak tua di hadapannya itu. Memperetelinya dengan pertanyaan yang
jelas memojokkannya. Diyanti semakin tidak mengerti maksud dan arah pembicaraan
mereka. Diyanti hanya bungkam dan mulai mengacuhkan pembicaraan pemilik warung
kopi itu.
“Kau menangis karena iba pada dirimu sendiri. Bukan karena
kau demikian sayang kepada kakakmu.” Sekali ini Diyanti tidak tahan dan hendak
beranjak dari tempat duduknya, membayar kemudian pergi. Tetapi orang tua di
hadapannya terus saja mencercanya dengan pernyataan dan pertanyaan yang semakin
tak mampu dijawabnya sekaligus menusuk ke dadanya yang dibenarkan salah satu
sisi dirinya.
“Bukankah setelah ini kau tidak lagi memiliki orang yang
selalu melindungimu, memenuhi kebutuhanmu dan akhirnya membuatmu kesepian,
kehilangan, dan kau merasa sendirian. Perasaan macam itu membuatmu menangis dan
mengasihani diri sindiri.”
Diyanti menatap wajah orang tua di hadapannya yang kini
mulai tertunduk lesu. Air mata di pipinya mulai mengering karena tersapu udara
dan panas mentari yang mulai beranjak naik. Diyanti mengerenyitkan dahi dan
berjuta pertanyaan ingin ia muntahkan di hadapan pemilik warung yang sok tahu
dan tidak memahami perasaannya. Namun sebelum Diyanti meluncurkan pertanyaan
itu, lelaki di hadapannya melanjutkan kalimatnya yang belum tuntas. Diyanti hanya diam, dia ingin tahu kalimat
apa lagi yang akan keluar dari mulut pemilik warung itu.
“Jadi siapa yang sesungguhnya kau kasihi? Kakakmu atau
dirimu sendiri?” Sesaat Diyanti terdiam kemudian dia merogoh uang dari sakunya,
menyimpannya di meja seharga kopi yang belum dia sentuh itu, lantas beranjak
pergi.
Pemilik warung itu mafhum dengan kondisi anak muda yang beberapa saat lalu duduk di
hadapannya. Ia pun sesungguhnya merasakan hal yang sama.
Seminggu yang lalu sebelum warung ini tutup, sebelum Diyanti
tidak nampak batang hidungnya di kampus. Pak Teno, lelaki pemilik warung itu
menemui keluarga dari orang yang menabrak putri semata wayangnya, dan ia hanya
bertemu kerabat jauhnya sedang Diyanti, adik dari orang yang menabrak putrinya
tak sadarkan diri ketika tahu bahwa selain seorang perempuan usia belia,
kecelakaan itu merenggut nyawa kakaknya yang mengendarai sepeda motor dan
terlempar sejauh 15 meter.
Selama seminggu terakhir Pak Teno menutup warungnya, begitu
juga Diyanti absen dari kelasnya dan otomatis tidak mengunjungi warung kopi
langganannya itu. Pak Teno hanya mengurung diri di rumahnya yang kini
benar-benar sepi, makanan disentuhnya tanpa nafsu, dia seorang diri di kota
besar ini. Dia merasakan kepahitan yang sama, setiap hari melewatkan hari
dengan melamun dan meratap. Sampai suatu hari ia tersadar betapa ia iba pada
dirinya yang kini sendiri. Ia sampai pada sebuah kesadaran bahwa manusia itu
mencintai dirinya sendiri dan mencintai orang-orang yang cinta kepadanya.
Bandung, Mei 2013




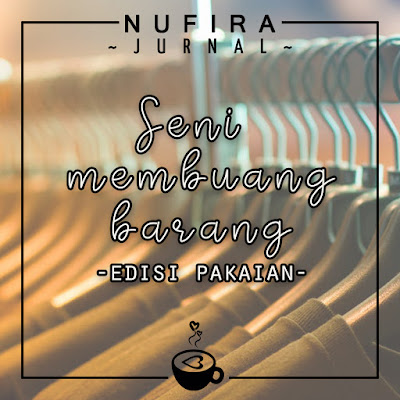


Comments
Post a Comment