DUKA SEBENTUK LENGKUNG SENYUM
Hari ini akan kutuntaskan
janjiku. Ini juga akan menggenapkan usahaku untuk membahagiakanmu semampuku.
Inilah yang akhirnya hanya bisa aku lakukan. Aku hanya bisa ikut berbahagia
melihat kau bahagia, Tantri.
Mentari nampak begitu terik pagi
ini, menyentuh lembut dedaunan. Kilatan cahaya yang terpantul dari bulir-bulir
embun di permukaan daun membuat cerah sekeliling. Sebelum akhirnya menguap ke
udara bergumul dengan sejuk angin.
Hari ini genap satu tahun aku
kembali ke kampung, setahun terakhir aku habiskan di kota untuk menyelesaikan
tugas akhir serta skripsi ku. Akhirnya hari ini datang juga, dulu aku mengira
ini akan menjadi mimpi buruk bagiku, tapi ternyata hanya masalah waktu aku bisa
menerima semua ini dengan hati yang lapang.
Jam menunjukan pukul sepuluh, bergegas aku panaskan motorku sebelum kemudian
meluncur menyusuri gang-gang yang dikelilingi pesawahan juga beberapa pemukiman
penduduk sebelum akhirnya melewati jalan utama beraspal. Hari ini jelas
spesial, jika bukan spesial untukku, hari ini adalah hari spesial bagi orang
yang spesial bagiku.
Aku mengenalnya sejak kami masih
bocah ingusan, kemudian
pertemanan kami berlanjut sampai kami menginjak bangku SMP dan SMA. Kami melewatkan
SMP di sekolah yang sama.
Saat istirahat, ketika
semua anak ramai menyerbu kantin kami bergegas menuju perpustakaan. Aku memang
tidak satu kelas dengan Tantri, tapi di perpustakaan sempit dengan buku yang
berdebu ini kami selalu bertemu dan membincangkan buku apa yang telah
kami baca. Sampai suatu hari di pertengahan kelas IX kami harus menelan
kekecewaan bersekolah
di kampung seperti ini.
“Yang ini udah.” Ujar Tantri
dengan nada kecewa seraya melemparkan buku itu ke raknya menimbulkan suara
sedikit gaduh diiringi debu yang terlempar ke udara.
Aku melihat ke sekeliling dan
menganggukan kepala kepada beberapa pasang mata yang memandang ke arah kami.
“Pelan-pelan nyimpennya bisa
kan?” ucapku seraya merapikan buku yang dia acak-acak sejak kami masuk ke
ruangan ini.
“Coba cari novel yang belum kita
baca! Udah semua kan?” seraya berdecak ia melangkah ke arah lain. Aku hanya
tersenyum miris di dalam hati, bukan hanya karena menertawakan nasib
perpustakaan sekolah kami yang minim buku bergenre fiksi untuk anak seusia kami
tapi aku menyadari satu hal bahwa kami kini sebentar lagi ujian, saatnya
membaca banyak buku pelajaran yang akan membantu kami menyelesaikan soal yang
akan menentukan kelulusan kami dari jenjang sekolah ini.
“Kita bisa belajar banyak hal
dari sebuah cerita, petualangan, atau kisah-kisah klasik, bukan hanya melulu
dari buku paket Yadin.” Itu jawabnya ketika aku utarakan pikiranku. Baginya
mudah saja menyelesaikan soal-soal di setiap ulangan dengan hanya bermodal
mendengarkan penjelasan guru, berbeda denganku yang tidak sejenius dia sehingga
mendengarkan penjelasan guru saja tak pernah cukup, aku harus membaca buku
referensi lain juga banyak bertanya padanya.
Hal itu berlanjut sampai aku SMA
dan kuliah, aku memang membaca banyak novel, tapi aku selalu memprioritaskan
bacaan lain yang berupa nonfiksi. Jarak kita yang jauh membuat intensitas
pertemuan kami berkurang. Ia melanjutkan kuliah di sebuah universitas
cabang yang berkampus di daerah kami. Sedang aku menempuh kuliah di sebuah universitas negeri di kota.
Ketika pulang ke rumah, aku
menyempatkan diri untuk mengunjungi dia di rumahnya yang masih berada di ujung
kampung kami itu, bedanya jika dulu rumah ini hanya satu-satunya sekarang sudah
banyak rumah disekitarnya. Aku memang cenderung jarang pulang, bukankah hari
ini jarak telah diringkus oleh alat komunikasi yang semakin canggih, kita bisa
mengetahui apa yang sedang dilakukan atau berbagi tentang apa yang dirasakan oleh
kerabat kita yang berada jauh dari kita hanya dari sebuah layar komputer atau handphone?
Di kali ke sekian aku mengunjungi
rumahnya, tak banyak yang kami lakukan atau obrolkan, aku biasanya hanya
mengantarkan pesanan bukunya dari kota.
“Ini dua buah novel yang
dikeluarkan oleh penulis yang sama dalam satu tahun ini.”
Dia terperangah mendengar
ucapanku. “Keren sekali, rasa-rasanya aku pun ingin menjadi penulis.” Ujarnya
sambil mengulum senyum. Tantri yang ku kenal sekarang memang begitu berbeda,
selain aku jarang menemuinya, komunikasi dari handphone pun seperlunya. Aku
menyadari bahwa kini dia telah tumbuh menjadi gadis yang dewasa dan matang. Aku
pun sering mempertanyakan, harus kusebut apa desiran yang merambati
dinding-dinding hatiku ketika mengingat namanya, menjumpainya seperti yang akan
kulakukan juga hari ini.
Motor yang kubawa meluncur di
kecepatan 20km/jam, sengaja aku melambatkan laju motorku. Berharap ada
tangan-tangan malaikat yang merubah keputusan hari ini, atau melambatkan waktu
yang meluncur deras, atau lemparkan saja aku ke tahun-tahun sebelum ini. Hanya
demi satu hal, agar aku tak pernah terluka juga melukai orang lain.
Selama perjalanan ini pun
kepingan kenangan berebut muncul mencari celah ke permukaan, mataku pun
dipenuhi bayangan-bayangan itu. Bunyi klakson juga bayangan kendaraan yang
menyalip melewati motorku mengantarkanku pada kilatan-kilatan kejadian yang
kulewati setahun lalu.
“Tidak ada persahabatan abadi
antara perempuan dan laki-laki.” Ujarnya di suatu hari setahun lalu, lewat
pesan yang muncul di layar handphone ku. Aku lebih dari paham apa yang dia
maksud. Selain itu dia pun memaksaku untuk pulang dalam waktu dekat ini, ada
hal yang harus ia bicarakan. Tapi aku masih sibuk dengan kuliahku yang sedang
padat-padatnya, aku menunda kepulanganku sampai libur semester dan aku dengan
lega meninggalkan kampus, melepas lelah sejenak dengan pulang kampung.
Sesampainya di rumah aku baru
sadar kalo aku melupakan sesuatu, sebuah novel terjemahan yang sudah lama tidak
terbit lagi. Aku pun segera menuju rumahnya untuk meminta maaf, ia hanya
tersenyum dan mengatakan bahwa ayahnya ingin berbicara denganku, aku merasa
keheranan, aku memang cenderung dekat dengan keluarganya ketika aku bertandang
ke rumahnya kakak juga ayah dan ibunya menyambutku dengan baik.
Tiba-tiba genangan air
menggantung di kelopak mataku mengingat hari itu, hari yang membuatku berhenti
menemui Tantri lagi, kalimat ayahnya itu jelas menujukan bahwa aku memang sudah
saatnya memilih. Tantri bukan lagi gadis kecil yang dulu kukenal, sudah ada
pemuda yang tertarik dan ingin melamarnya. Dan aku, apa dayaku selain berdamai
dengan masa lalu yang kami lewati bersama yang seharusnya indah untuk dikenang menjelma
duri-duri yang menusukku, membuatku meringis tak berdaya.
Aku mempercepat laju motorku, di
depan sana terlihat keramaian, di sebuah rumah di ujung kampung kami, di
pinggir sungai dengan air bening dan bongkahan batu yang tersebar terlihat dari
permukaannya.
Aku memarkir motor di tempat yang
disediakan, merapikan rambut juga kemejaku, dan mengeluarkan kotak berbalut sampul warna biru safir, sebuah
buku terjemahan yang belum sempat aku berikan, novel dengan setting keindahan sebuah pedesaan
di dataran Eropa. If
Only They Could Talk karya James Herriot.
Kulangkahkan kaki menuju ruang
resepsi,
rumah itu kini disulap dengan ornamen yang cerah ditambah jambangan besar dengan
bebungaan yang
didesain untuk mempercantik ruangan. Degup jantungku semakin kencang, tangan juga kakiku bergetar,
kuhela nafas panjang melihat sosok gadis yang terlihat anggun itu bersanding
dengan seorang lelaki yang beruntung meminangnya. Terlihat senyum mereka
mengembang ketika satu persatu menyalami tamu yang hadir. Beberapa detik aku
terpaku, rasanya bumi berhenti berputar, ada yang bergemuruh di dada ini
menyeruak tercekat di kerongkongan hingga membuat mataku mengembun, tapi kucoba
tersenyum selebar mungkin, mendekati pelaminan itu.
Tantri yang melemparkan
pandangannya padaku pun kulihat terkaget. Aku jelas melihat perubahan rona wajahnya, senyumnya
menguncup dan matanya bening sebening kaca sebelum akhirnya meluncurlah butiran
air mata di pipinya. Aku tak menghiraukan air matanya, aku masih tersenyum dan
memberikan kotak itu padanya. Ia menerima dengan tangan bergetar, kemudian
kusalami lelaki yang telah menjadi suaminya itu. Mengucapkan beberapa doa,
kemudian berbalik dan pergi meninggalkan ruangan itu, aku lurus
berjalan menuju motorku dan melaju dengan cepat. Meninggalkan rumah ini juga
meninggalkan masa laluku yang terjebak di belakang sana.
Berbahagialah Tantri.
By: Nufira Stalwart
Kamar Remang-remang @Violet79




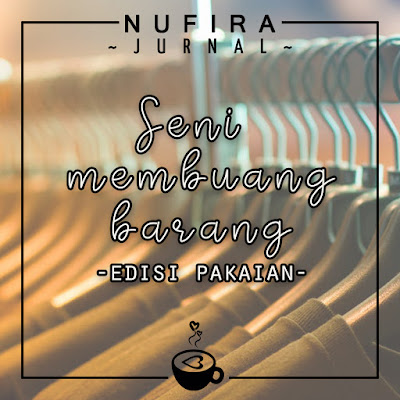


Comments
Post a Comment