Tibet
Hari ini, dengan cuaca cerah di sebuah saung beratap jerami.
Aroma kopi menyeruak, perlahan menelusup ke rongga hidungku. Kopi
yang bijinya ditumbuk, murni tanpa tambahan apapun, termasuk butiran
gula. Pahit memang, tapi kekuatan aroma dan kepekatan pahitnya itu yang
membuatku tak bisa tak menyentuhnya walau sehari. Kuteguk ia perlahan.
Lalu kualihkan kembali pandangan pada laptop yang berdenyar. Kelip-kelip
hijau terlihat di lampu indikator modemku. UMTS. Kampung ini masih
perawan, belum tersentuh sinyal yang lebih tinggi dari itu. Kuseret
pointer menuju bookmark toolbar mail, klik, beberapa saat kemudian muncul list unread mail. Ada email baru dari nama yang kukenal. Belum sempat kubuka, aku terdiam lama membaca subjek email itu.
***
Tujuh tahun lalu, setelah lima menit bel istirahat sekolah berbunyi.
“Aku ingin ke Tibet!” Setengah berteriak, kalimat itu meluncur dari
seseorang bersuara cempreng yang duduk di sampingku. Teriakan yang tidak
lantas membuat orang sekitar menoleh atau melemparkan pulpen padanya
seperti di film-film, sekalipun sama, ini perpustakaan.
Aku menoleh padanya sesaat. “Makin gila aja ni anak.” Bagaimana tidak
kubilang gila, kemaren dia bilang ingin ke Bukit Tinggi gara-gara baca
cerita yang berlatar di kota itu. Kemarin-kemarinnya lagi ia ingin
berpetualang gara-gara baca Tom Sowyer nya Mark Twin. Tapi akulah yang
lebih gila, karena masih saja mau mendengarkan racauannya.
“Pokonya aku bakalan ke Tibet Dam! Tibet! Macam Tintin di cerita
ini.” Ujarnya kemudian seraya memperlihatkan buku yang sedang dibacanya.
Tintin di Tibet.*
 Kenapa pula buku itu harus nyelip di antara sekian rak di
perpustakaan ini yang didominasi oleh buku teks? Perpustakaan yang tak
ada larangan ngobrol disini, riuhnya tak kalah dengan kantin di belakang
sekolah. Perpustakaan yang merangkap sebagai tempat diskusi anak-anak
organisasi di eskul, tempat belajar kelompok hingga tempat curhat yang
paling nyaman karena didesain untuk lesehan. Lebih tepatnya karena tak
tersedia meja atau kursi disini. Perpustakaan di sebuah sekolah di ujung
kabupaten Bandung.
Kenapa pula buku itu harus nyelip di antara sekian rak di
perpustakaan ini yang didominasi oleh buku teks? Perpustakaan yang tak
ada larangan ngobrol disini, riuhnya tak kalah dengan kantin di belakang
sekolah. Perpustakaan yang merangkap sebagai tempat diskusi anak-anak
organisasi di eskul, tempat belajar kelompok hingga tempat curhat yang
paling nyaman karena didesain untuk lesehan. Lebih tepatnya karena tak
tersedia meja atau kursi disini. Perpustakaan di sebuah sekolah di ujung
kabupaten Bandung.
“Caranya?”
“Aku akan menabung.” Ujarnya mantap.
Esok lusa, kutemukan selonjor bambu menggantung di kamarnya, dengan
lubang sebesar uang logam di atasnya. Kau tahu, suhunya yang lembab
membuat kau hanya bisa menyimpan uang logam ke dalamnya. Coba saja kau
masukan selembar uang kertas ke dalamnya, ketika kau membukanya uang
kertas itu telah berjamur. Jadi hanya uang logam dengan nilai seribu
yang paling besarnya.
***
Lima tahun yang lalu, ketika telepon genggam masih barang mewah.
“Kau betah sekali tinggal di kampung halaman kita.” Ujarnya dengan terkekeh di ujung pesawat telepon sana.
“Aku memang teramat cinta pada tempat ini. Aku yakin kampung kita tak kalah indah dengan Tibet.”
“Oiya, feelingku berkata, tahun depan aku ke Tibet.”
“Bah, kau bahkan bilang gitu, setahun, dua tahun, tiga tahun lalu.”
“Ya, kalo tidak tahun ini mungkin tahun depan, atau tahun depannya
lagi. Setelah omset penjualanku cukup untuk menambah tabungan kesana.”
Tambahnya sambil kembali terkekeh.
Dia memang seorang enterpreneur sejati. Pertama kali aku mengenalnya,
tak pernah aku tahu bahwa aneka gorengan yang laris manis setiap
istirahat di kantin Bu Teti itu adalah bikinan ibunya. Aku mengetahuinya
seteleh tiga tahun mengenalnya, mengenal kebiasaannya yang selalu tiba
paling pagi di sekolah untuk mengantarkan gorengan, lantas pulang
sekolah tak pernah keluyuran kemana-mana tetapi menjinjing dua keresek
penuh bahan baku masakan di kanan kiri tangannya yang ia beli dari
sebuah grosir dekat sekolah.
Dia tak pernah cerita. Gengsi mungkin. Hal yang wajar kukira untuk
seusia anak SMP. Namun hari ini bisnisnya itu terus berlanjut, meski
bukan lagi ibunya yang membuat, tetapi pemilik kost tempat ia tinggal
selama ia mengenyam pendidikan di sebuah sekolah ternama di tengah kota
Bandung
“Enterpreneur itu bukan cuman punya kemampuan membuat produk, namun juga memasarkan produk. Marketing man!” aku hanya mengangguk tanda setuju. Entah dari mana ia dapatkan kalimat itu.
***
Dua tahun lalu, aku lupa musim apa saat itu.
Yang aku ingat kepulangannya dari kota ke kampung kami, maka di hari
itu ia mengunjungi rumahku membawa atlas besar. Ini kegilaan ke sekian
dan ke sekiannya lagi selama kami berteman akrab.
Atlas itu dilengkapi keterangan tempat dan budaya serta kekhasan tempat tersebut.
“Air terjun ini, berapa tingginya? Aku lihat tak lebih tinggi dari Curug Malela.”
“Niagara! Aku tak tahu pasti berapa tingginya, tapi untuk melihatnya
kau perlu melintasi ratusan negara dari sini pakai pesawat.”
“Ah, ngapain jauh-jauh? Hanya 50KM dari sini ada kopiannya.”
“Jelas beda, butuh perjuangan lebih untuk mencapainya.”
“Lalu mengenai Tibetmu? Kau batalkan dan menggantinya dengan pergi kesini.”
“Oh tentu tidak, aku akan mengunjungi keduanya.”
Aku menarik bibirku ke sebelah kanan saja. Senyum tak seimbang. Mana
mungkin? Aku tahu, untuk hidup saja ia perlu menjajakan gorengannya. Apa
pula dengan khayalan-khayalan itu.
***
Hari ini, ketika hanya ampas yang tersisa di gelasku.
Aku di Tibet. Itulah subjek emailnya padaku, kulihat di sampingnya,
email delapan jam yang lalu. Ku klik dengan jemari bergetar. Muncullah
fotonya memakai pakaian tebal dan sarung tangan dengan selonjor bambu di
tangan kanan dan satu bakwan di tangan kiri. Dua benda yang paling
akrab dengannya. Latar belakangnnya tenda-tenda bertebaran seperti
jamur, dan sebuah plang Everest Base Camp 5.200mdpl. Dia menulis:
“Adam, kau mengenal dua benda ini? Mereka mengantarkan aku ke Tibet Dam.”
Nb: Kau pasti tahu tabunganku tak sebanyak itu hingga
menyampaikan aku ke atap dunia. Seminggu yang lalu aku tiba di China
untuk mengikuti students exchange.
Aku mengambil gelas di hadapanku, hendak kuseruput, namun gumpalan hitam itu bergerak perlahan mendekati ujung bibirku.
*Kalimat ini terinspirasi dari catatan perjalanan Daniel Mahendra berjudul Perjalanan ke Atap Dunia



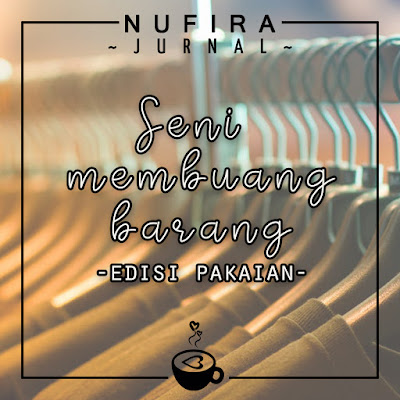


cool teh! keep writing... :D
ReplyDelete