Dua Jenis Film Adaptasi
“Don’t judge
the book by its movie.”
Sebuah ungkapan
yang tak mudah untuk diaplikasikan. Bagaimana mungkin kita tidak membandingkan
cerita yang kita imajinasikan dalam novel dengan cerita yang divisualkan dalam
sebuah film? Tentu saja celetukan semacam “Kok beda ya sama novelnya?” atau
“Lebih rame filmnya.” sering terdengar usai menonton film yang diadaptasi dari
novel. Tak sedikit juga yang merasa kecewa setelah seseorang menonton film dari
novel favoritnya. Padahal, tentu saja yang paling menunggu film adaptasi itu
kebanyakan adalah penyuka novelnya.
Hal ini juga
penyebab sebuah film adaptasi tak pernah sepi peminat. Sebab biasanya novel
yang difilmkan adalah novel yang sukses di pasaran dan membuat orang penasaran.
Film adaptasi juga telah memiliki pasar sendiri yaitu para pecinta novelnya
yang menunggu film adaptasi tersebut. Sekalipun biasanya mereka yang paling
sering dikecewakan.
Sebagai orang
yang sesekali mengikuti film yang diadaptasi dari novel, saya kerap bertanya,
sebenarnya bagaimana seharusnya sebuah film adaptasi dibuat? Setelah melewati
diskusi panjang dengan beberapa orang, akhirnya saya menyimpulkan bahwa sebuah
film adaptasi setidaknya dikelompokkan menjadi dua, pertama film yang “setia”
dengan novelnya, dan film yang “mengkhianati” novelnya. Kejam banget bahasanya -___-
Film yang setia,
sekalipun tidak sampai 100% mampu menginterpretasikan konten dalam novel ke
dalam sebuah film, setidaknya pembuatnya berusaha untuk membuatnya semirip
mungkin dengan novelnya. Film yang masuk ke dalam kategori ini misalnya Harry
Potter and the Deathly Hallows (2010) part 1 dan 2. Kebetulan saya menonton
film ini dulu baru baca novelnya. Dan saya merasa tidak begitu terhibur membaca
novelnya sebab sebagian besar cerita telah saya dapatkan dari filmnya,
sekalipun ada sebagian detail yang tidak ada dalam filmnya.
Kategori kedua
adalah film yang mengubah banyak cerita di dalam novelnya. Sebagian besar yang
saya tonton masuk ke dalam kategori ini. Sekalipun saya tetap membuat katogeri
lain yaitu film adaptasi yang mengubah banyak cerita tetapi tetap berhasil dan gagal
total. Tentu saja ukuran berhasil dan tidaknya juga subjektif, setidaknya
ukuran menurut saya yang awam dengan masalah film.
Untuk novel dalam
negeri, sebut saja Ayat-ayat Cinta (2008). Waktu SMA, saya adalah salah
satu pembaca novel AAC yang menunggu filmnya tayang. Tetapi saat menonton
filmnya, saya merasa (sependek pengalaman saya mengikuti film adaptasi) itu
adalah film terburuk yang pernah saya tonton. Bukan hanya karena cerita atau latar
yang berubah tetapi karakter tokoh-tokohnya benar-benar berubah. Film dalam
negeri lain yang saya tonton adalah Laskar Pelangi (2008) dan Sang
Pemimpi (2009). Saya menganggap bahwa novelnya lebih indah. Karena saya tidak
bisa berbuat apa-apa, maka saya memutuskan untuk berhenti menonton film
adaptasi dari novel dalam negeri. Misalanya, saya tidak menonton Edensor (2013),
Filosofi Kopi (2015) apalagi Supernova Ksatria, Puteri dan Bintang
Jatuh (2014) dari novel Dee, karena alasan-alasan tersebut.
Bukan berarti
film adaptasi di dalam negeri tak ada yang bagus. Saya menilai Perahu Kertas
(2012) salah satu film yang lumayan bagus. Mungkin karena film ini dibagi dalam
dua part sehingga ruang lebih luas dan cerita bisa dibuat lebih mendalam.
Untuk film
adaptasi luar, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004) adalah
salah satu film yang saya suka. Saya rasa film itu sungguh istimewa dibanding seri
Harry Potter yang lain. Setelah saya telusuri ternyata film ketiga ini digarap
oleh sutradara yang berbeda dengan dua film sebelumnya ataupun lima film
setelahnya. Dalam film ini, tidak ada scene yang sia-sia, bahkan saat menyorot
pohon yang bergerak pun demi mendukung cerita. Sekalipun saya tahu, ada banyak
detail yang dihilangkan tapi nggak mengurangi esensi cerita. Ini juga salah
satu film yang sering saya tonton ulang dan hampir nggak pernah bosan.
Film lain yang
saya suka adalah The Giver (2014). Bagi siapapun yang ingin menonton
filmnya tetapi belum membaca novelnya, saya sarankan baca dulu novelnya deh. Sebab
ada hal spesial di dalam novel yang hanya bisa kita nikmati dengan baik jika
kita membaca novelnya. Saya suka novelnya, sebab ini adalah novel distopian
klasik, nenek moyang dari cerita-cerita distopian setelahnya (termasuk Divergent
series). Kekhasan distopian klasik yaitu lebih kuat pada pesan daripada
actionnya.
Sebenarnya saya
tidak begitu antusias saat novel ini difilmkan, tetapi ternyata filmnya
menarik. Saya bahkan tidak keberatan saat terjadi perubahan karakter, setting
dsb. Karena ternyata hasilnya lebih bagus. Misalnya saja karakter Fiona dan Asher,
dua teman baik tokoh utama yang pekerjaannya diubah, tetapi justru mendukung
cerita dan pergerakan karakter utama tetap menjadi fokus penonton.
Lalu, adakah film
adaptasi yang filmnya lebih bagus? Ada! Menurut saya, salah satu diantaranya
adalah The Hobbit. Filmnya lebih rame, banyak eksplorasi di sana sini
dibandingkan dalam novel yang cenderung monoton. Mungkin karena film ini dibagi
menjadi 3 part, seperti yang saya ungkapkan sebelumnya, ruangnya lebih luas.
Kelebihan filmnya adalah banyaknya action sedangkan kekuatan novelnya ada pada detail.
Tentu saja ada detail cerita dalam novel yang tidak akan didapatkan oleh orang
yang hanya menonton filmnya.
Film lain yang saya
tonton dan justru membuat saya kecewa adalah Insurgent (2015). Saya
rasa, karakter Tris sebagai tokoh utama malah terlihat lemah (saya memang tidak
tahu banyak masalah acting tapi pemeran Tris tidak bisa mengimbangi kekuatan
karakter Four), juga karena penggambaran Amity yang kurang mendalam (sebab ini
adalah faksi favorit saya haha), ditambah ada pesan penting di ending yang
seharusnya muncul tetapi tidak ada. Detail itu bahkan kembali muncul di novel Allegiant
paragraf pertama tetapi diabaikan di film Insurgent (2015). Saya
menunggu sampai akhir tetapi tidak muncul. Bagi siapapun yang membaca novel dan
menonton filmnya tentu mengerti apa yang saya maksud. Insurgent (2015) juga
melakukan perombakan besar dalam cerita. Tetapi ada hal yang kemudian berkesan
bagi saya yaitu efek digitalnya yang cukup menghibur.
Well, saya masih
bisa menerima sebuah film adaptasi yang ceritanya berubah atau justru membosankan
karena sama persis dengan novelnya. Tetapi, pada akhirnya, bisakah kita (saya)
menjadikan novel sebagai dirinya sendiri dan film sebagai dirinya sendiri?
(Ditulis untuk
memenuhi tantangan menulis #10DaysKF hari kelima tentang 3 film yang paling
berkesan.)
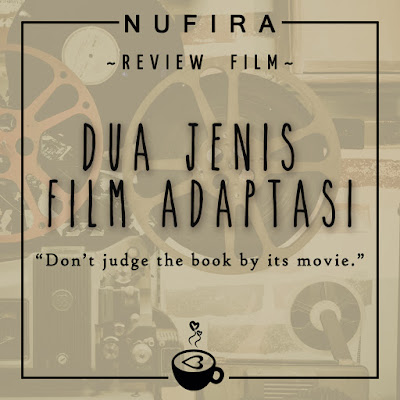





Aku setuju banget yg AAC itu. Baca novelnya terus nonton filmnya, sumpah sakit hati. Sampai kusumpah2im tuh sutradaranya, saking jengkelnya ga sesuai ekspektasi. Hahaha.
ReplyDeleteHarry Potter emang the best untuk kategori film adaptasi, meski sutradaranya ganti2, tapi rasa Harpotnya tetep ada.
Ngg... aku nonton Divergent series ga pake baca novelnya. *lalu menyesal
Ngg... mba, bedanya distopian dengan embel2 lainnya sama distopian klasik itu apa ya? Hehehe
Aku nggak merasakan spirit novel AAC muncul di filmnya. Novel Divergent lumayan bagus, aku suka tapi lebih suka The Hunger Games. Sepemahaman aku, distopian itu cerita yang berlatar dunia baru, bukan jenis dunia dengan tatanan yang kita kenal. Aku bilang klasik karena buku terbitan lama sih hehe khasnya buku klasik tu masih relevan dan menyenangkan dibaca hingga saat ini.
Delete