Ketika Hujan Turun (Suara Pemred, 29 Januari 2017)
Oleh: Nufira S.
Entah kapan terakhir kali Masni jatuh demikian lelap dalam tidurnya seperti
kali ini. Dia bermimpi kedua anaknya dibawa pergi oleh seseorang dan menghilang
di balik kabut asap. Tangan kiri Masni mendekap erat anak ketiganya yang belum
genap enam bulan, mengerang di pangkuannya. Sedang tangan satunya lagi
menggapai-gapai meraih bayangan dua anaknya yang terus berjalan ditelan
pekatnya asap, namun yang dia dapatkan hanya kekosongan.
Begitu pula saat ia terjaga, sambil mengerejapkan mata, kedua tangannya
serta merta menggapai-gapai mencari ketiga anaknya yang biasa tidur di
sekitarnya. Anak paling bungsu, menempel rapat di pelukannya, sedang dua
anaknya yang lain tidak ada di sana. Masni tersengat.
Orang pertama yang harus dicari Masni adalah suaminya sendiri. Tanpa perlu susah
payah dicari, Masni melihat lelakinya itu tengah duduk menekuk kepalanya sambil
memeluk lutut di seberang kamar. Masni bangkit seketika, menghambur ke arah
suaminya lalu mengguncang-guncangkan lengan lelaki itu, hingga
memantul-mantulkan rambutnya yang bergelombang.
“Dimana anak-anakku?
Kau bawa kemana Jantan dan Noni?” Masni meronta-ronta sambil menangis memecah kesunyian di sekitar mereka.
Tadi malam, sebelum Masni
tertidur amat lelap yang tak pernah dia alami tiga bulan terakhir ini dan kemudian dia sesali, mereka masih makan
bersama. Masni menghidangkan manggalo
mersik[1], makanan khas suku
Sakai di pedalaman Riau. Di hadapan anak-anaknya dia tak menampakan wajah
khawatir melihat persediaan manggalo
mersik yang
tinggal sedikit.
“Untung persediaan manggalo mersik masih cukup. Sengaja tidak Ibu
jual ke tetangga biar kita tetap bisa makan,” ucap Masni sambil membagi
makanan.
Biasanya, manggalo
mersik disajikan bersama gulai ikan atau
sayur-sayuran. Tetapi di masa sulit
seperti ini, mereka harus puas mengunyah makanan yang menyerupai kerak nasi yang bergumpal kecil dan keras itu dalam diam, tanpa lauk pauk. Anak-anak pun tak rewel, mereka makan apa yang
dihidangkan ibunya. Setelah selesai
makan, mereka kembali berbaring di samping ibunya sambil sesekali
mengeluhkan napas yang sesak atau
badan yang gatal-gatal.
Pada hari-hari biasa, sebelum
bencana kabut asap melanda
dusunnya, Masni kerap pergi ke hutan untuk mencari ubi manggalo. Ubi beracun
yang mesti diolah terlebih dahulu
sebelum dimakan untuk menghilangkan racunnya. Kemudian dia jajakan pada warga sekitar
dengan harga murah, namun
bisa cukup untuk menutupi kebutuhan
keluarga disamping mengandalkan suaminya yang berladang dan berburu ikan di sungai.
Kini, suami Masni tidak bisa lagi mengolah ladang atau menangkap ikan di sungai sebab
jarak pandang yang terbatas karena
kabut asap, serta sungai yang airnya surut karena kemarau tak banyak menghasilkan
ikan. Namun, suaminya itu jarang tinggal di rumah. Lelaki itu kerap jengah mendengar anak-anaknya meringis
kesakitan sambil menunjuk dada. Terkadang anaknya yang masih bayi menangis lemah
namun masih bisa diredakan jika diberi susu ibunya.
Beberapa hari terakhir, sejak
terjadi perbincangan serius antara
suami istri itu. Masni tak pernah menjauhkan ketiga anak-anaknya dari jangkauannya. Noni yang sudah
bersekolah kelas tiga SD, sudah
beberapa minggu tak masuk sekolah.
Pun tak pernah dia izinkan kemana-mana.
Begitu juga dengan Jantan, anak lelakinya yang biasanya begitu cerewet dan
lincah memasuki usia lima tahun kerap merengek meminta bermain-main di luar rumah
tak pernah diizinkannya. Sekalipun, Jantan hanya duduk-duduk di beranda rumah, segera dipanggilnya untuk tetap di
sisinya.
Anak-anak seusia mereka tentu bosan tinggal di rumah seharian. Mereka kerap
memaksa untuk bermain di luar bersama anak-anak lain. Tetapi, Masni membujuknya
untuk tak keluar dengan banyak cara. Misalnya, bercerita tentang hantu yang
berkeliaran sepanjang waktu, karena siang hari matahari tak kelihatan muncul.
Mendengar cerita itu mereka akhirnya menurut dan merapatkan dirinya di tubuh
ibunya yang semakin kurus.
Pada malam hari, Masni juga selalu terjaga. Jarang sekali
dia terlelap tidur. Bukan hanya karena dia kesulitan tidur, tetapi juga karena sedikit-sedikit salah satu anaknya
terbangun mengeluhkan rasa sakit dan
Masni harus mengelus-elus anaknya hingga mereka tenang.
Kabut asap yang menyelimuti
dusunnya akibat kebakaran hutan telah begitu banyak mengusik ketenangan
hidupnya. Bukan hanya kini dia tidak lagi bisa mencari ubi manggalo ke hutan, suaminya juga tidak bisa berladang dan
mencari ikan. Anak-anaknya tidak bisa bermain dan bersekolah. Terlebih dengan
persediaan makanan yang semakin menipis, dia tidak bisa memberi makan anak-anaknya hingga kenyang.
Bukan sekali dua kali dia
membiarkan anak-anak dan suaminya makanan lalu dia mengambil sisanya yang tinggal sedikit. Masni kemudian memakannya
perlahan-lahan, sedikit demi
sedikit agar dikira bagiannya sama seperti mereka. Suaminya yang melihat ini
tentu tak bisa dibodohi dan tak kuasa melihatnya. Dia memberikan
bagiannya untuk dibagi dengan istrinya. Sekali waktu dia pernah mengambil dari
jatah anak paling besar untuk diberikan pada ibunya, yang tentu membuat anak itu merengek
melihat makanannya berkurang.
Mereka pun seolah-olah hidup seorang diri. Sebab
saat melongok ke luar pintu, tak dilihatnya lagi rumah tetangga yang hanya dibatasi kebun
atau lahan kosong. Kabut asap telah mengepung dan memisahkan mereka dari kehidupan.
Maka, ketika suatu malam Masni terlelap sejenak dan meraba-raba menghitung jumlah
anaknya dan ia hanya merasakan ada satu anaknya di sampingnya, dia begitu kaget
dan tersentak. Orang satu-satunya
yang harus bertanggung jawab ketika dua anaknya direnggut dari sisinya adalah
suaminya sendiri.
“Aku ibunya. Aku yang akan mengurus dan memberi mereka makan!” Raung Masni. Yang tetap ditanggapi dengan bungkam oleh
suaminya.
Jeritan dan raungannya Masni pagi buta begini barangkali
telah membangunkan tetangganya yang berjarak beberapa meter dari rumahnya.
Namun, tak ada yang penasaran
menengok mereka, untuk
sekadar bertanya apa yang telah terjadi. Peristiwa semacam ini kerap terjadi
dan orang-orang tahu apa yang mereka persoalkan. Namun, tentu tak akan ada yang menyangka perihal mimpi Masni tentang dua anaknya
yang ditelan asap dan mendapati dua anaknya benar-benar menghilang dari
sisinya.
“Ayah macam apa kau, yang begitu tega melakukan ini kepada anak-anaknya sendiri!” Masni berteriak sekuat tenaga di depan telinga suaminya yang terus
membatu. Berharap suaminya bergeming.
Hingga perlahan, suaminya mengangkat kepala. Tanpa berani menatap mata
istrinya yang telah memerah, atau rambutnya yang kusut masai. Dia membuka
mulutnya dengan suara bergetar.
“Justru aku tak tega melihat mereka.” Air mata telah menggenang
di kelopak mata lelaki itu. “Aku
mencintai mereka. Setidaknya saat ini, mereka sudah tidak lagi kelaparan dan
mengeluh sakit dada.” Tangisan suaminya akhirnya pecah. Tangisan ini mungkin telah coba dia tahan
sekuat tenaga. Entah apa yang sesungguhnya ia tangisi, apakah penyesalan pun
terselip di sela-selanya?
Masni tergugu, dia menatap suaminya dalam diam. Bukan karena kini suaminya
meraung-raung dan bersimbah air mata. Dia mendengar suara yang begitu asing
sekaligus dia rindukan.
Tidak mungkin. Pikir Masni.
Suaminya yang merasakan hal serupa menghentikan tangisannya. Dia menatap
Masni yang kini mematung. Mereka sama-sama mendengar suara hujan
menandak-nandak di luar rumah.




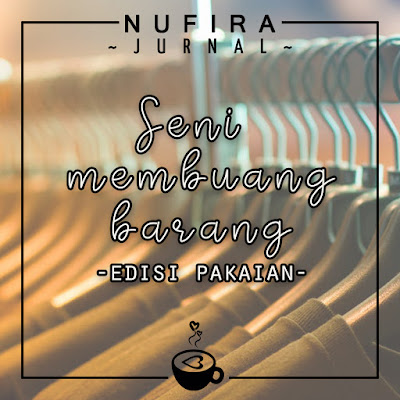


Comments
Post a Comment