Tentang Pohon yang Ikut Bersedih
Menjumpai
Kinanthi
Hope
Apa
kabar, Thi? Suratku datang lagi. Jarak dari surat ini dengan surat sebelumnya itu setahun. Lama yah aku tidak berkirim kabar? Kenapa aku tiba-tiba berkirim surat
padamu? Aku juga tak tahu, kenapa di saat-saat seperti ini teringat padamu. Apakah ini semacam pelepasan, pembebasan, atau menyelamatkan separuh
hatiku yang masih tersisa? Seperti waktu itu.
Aku
tiba-tiba tidak tahu harus memulai cerita dari mana. Baiklah, aku mulai dari... aku sudah
pindah kerja, Thi. Di tempat kerjaku yang baru, ruanganku di lantai dua, meja
kerjaku tak jauh dari jendela. Jadi aku bisa bebas menatap langit. Kau tahu,
aku menyukai langit dengan segala atraksinya, dengan semua benda-benda yang
bertebaran di sana.
Aku
kerap mengamati pesawat yang kebetulan lewat, terbang dengan lambat sampai
menghilang di balik pandanganku. Aku sering mengamati rinai hujan. Aku menyukai
bunyi hujan, di laptop aku menyimpan beberapa lagu yang dilengkapi dengan suara
rincik hujan. Aku pernah mengatakan pada seseorang bahwa aku suka hujan di pagi
hari. Kamu tahu dia jawab apa, Thi?
Dia
bilang, “Aku suka mandi di pagi hari”
Dia
memang senang bercanda, Thi.
Tapi
saat aku bilang lagi, aku suka bunyi hujan, dia bilang hujan gak ada bunyinya.
Aku
bilang, “Kalo gak ada bunyinya, gak mungkin ada lagu ‘tik, tik tik bunyi
hujan...’ kan?” Aku teringat lagu masa kecilku.
“Coba
ke pantai, ga akan ada bunyi hujan!” Katanya. Aku memang jarang ke pantai, Thi.
Jika diminta memilih antara pantai dan gunung. Aku akan memilih gunung.
Namun
sekali waktu kami pernah ke pantai dan dia membuktikan bahwa hujan di sana
tidak ada bunyinya. Hujan menjelma menjadi sesuatu yang tidak lagi kukenali.
Sunyi. Ya, sunyi. Aku kemudian berpikir, apakah hujan adalah jelmaan kesunyian,
atau kesunyian adalah jelmaan hujan? Hmmm....
Ah,
Thi, kenapa aku malah berbicara tentang dia. Bukan ini yang kurencanakan
untuk kuceritakan padamu. Tetapi kau tahu kan, saat menulis, jemari lebih
berkuasa dari pikiran, dan itu sungguh tak bisa dihindari.
Sampai
dimana kita tadi? Oya, aku menyukai langit. Mataku sering tertuju pada jendela.
Di luar jendela, di sebrang jalan sana, ada sebatang pohon berdiri kokoh. Warna
daunnya seperti warna daun pada umumnya. Hijau. Suatu hari semua berubah! Bukan,
Thi. Demi Tuhan, bukan karena negara api menyerang! Entah kenapa, dedaunan dari
pohon itu berwarna jingga. Jingga, Thi, itu warna kesukaanku setelah hitam dan
sebelum hijau toska.
Awalnya
hanya pucuk-pucuknya, lalu beberapa hari kemudian seluruh daun di pohon itu berwarna jingga.
Anehnya hanya satu pohon itu saja yang berwarna jingga. Deretan pohon di jalan
itu daunnya masih hijau. Aku memandangnya sesering yang aku mau. Sekali
waktu, datang angin besar lalu daun-daun itu berhamburan ke segala arah. Aku
terperangah dari balik jendela. Ini seperti musim gugur di daerah sub tropis,
seperti di foto-foto yang banyak aku koleksi.
Pohon
itu menggugurkan daunnya, indah sekali, Thi. Apalagi saat senja datang.
Matahari senja yang entah kenapa beberapa hari ini terlihat lebih indah,
menerpanya. Aku menyukai senja seperti aku menyukai musim gugur. Apakah itu
alasan aku menyukai warna jingga? Ataukah karena aku menyukai warna jingga maka
aku menyukai musim gugur dan senja. Ini penting, Thi. Selalu ada sebab akibat
dari segala sesuatu kan?
Lanjut ke pohon itu, Thi. Hari Senin kemarin, saat aku sampai kantor aku dikagetkan karena pohon itu
sudah nyaris gundul. Tak ada daun yang tersisa, kecuali sedikit di batang bagian bawahnya. Dua hari aku tidak masuk kantor
dan pohon itu sudah sama sekali berubah.
 |
| Ini pohon yang kumaksud, Thi. |
Pertanyaannya,
kenapa hanya satu pohon itu? Tidak dengan pohon-pohon lain. Apakah sebenarnya
semesta sesungguhnya sedang berempati pada seseorang yang mengaguminya? Beberapa
waktu terakhir aku kerap memandangi pohon itu setiap kali aku merasa bersedih. Akhir-akhir
ini aku sering bersedih, maka semakin sering aku memandang pohon itu. Apakah
mereka pun merasakannya? Apakah kesedihan dari sorot mataku dapat dibaca?
Ini
serius, Thi, aku pernah membacanya di sebuah buku bahwa tumbuhan bisa mengerti
bahasa kita. Nggg.... maksudnya menangkap energi dari bahasa yang kita gunakan.
Jika kita berpikir atau berbahasa positif, itu akan berpengaruh positif pada
tanaman di sekitar kita. Begitu juga sebaliknya.
Aku
memang bukan satu-satunya orang yang berada di dekat pohon itu, aku juga bukan
satu-satunya orang yang bersedih. Tetapi aku merasa, pohon itu sedang
menunjukkan sesuatu padaku.
Bahwa
cepat atau lambat daun itu akan gugur. Bahwa cepat atau lambat seseorang yang
tidak tepat untuk hadir dalam kehidupan kita, akan direnggut. (Apakah
asosiasiku ini tepat, Thi?) Karena setelah ini ada kehidupan yang lebih keras.
Musim kemarau barangkali. Katakanlah begitu. Sehingga pohon itu bisa bertahan
dengan persediaan air yang minim, jika dan hanya jika dia menggugurkan daunnya.
Sesuatu yang bahkan telah menjadi bagian dari dirinya.
Benar,
Thi. Aku merasa pohon itu tengah mengajarkan aku tentang melepaskan, merelakan
demi menjaga keberlangsungan hidupku. Maka seperti pohon itu yang akan tetap
kuat sekalipun tanpa rimbun dedaunan. Aku harus tetap kuat sekalipun harus melepaskan
seseorang yang pernah jadi miliku --atau bersamaku. Mungkin manis yang urung kereguk bersamanya
memang bukan jatahku. Sekalipun melepaskannya berarti membawa lebih dari
separuh hatiku bersamanya. Menyisakan separuh hati yang tersisa, separuh hati yang harus tetap kujaga. Aku harus
merasa utuh dengan apa yang tersisa. Merasa cukup dengan apa yang kupunya. Hmmm... aku menarik napas panjang ketika sampai di bagian ini.
Begitu, Thi. Aku tiba-tiba merasa demikian sedih. Kusudahi
dulu suratku ya, Thi. Kapan-kapan aku akan
berkirim surat lagi. Semoga selanjutnya kabar bahagia.
Selamat
Malam, Thi.
*Saat menulis judul tulisan ini, saya teringat dengan cerpen Guntur Alam yang berjudul Sebatang Pohon yang Tak Bahagia
**Tulisan ini dibuat dalam rangka (Kembali) #MenantangDiri #30HariMenulis
*Saat menulis judul tulisan ini, saya teringat dengan cerpen Guntur Alam yang berjudul Sebatang Pohon yang Tak Bahagia
**Tulisan ini dibuat dalam rangka (Kembali) #MenantangDiri #30HariMenulis



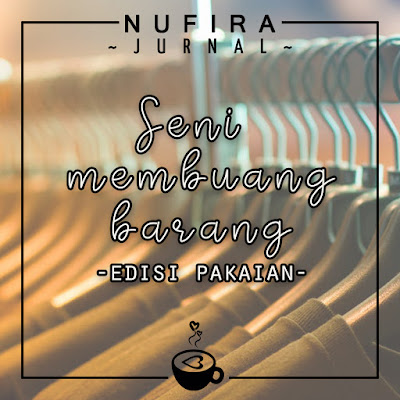


Comments
Post a Comment